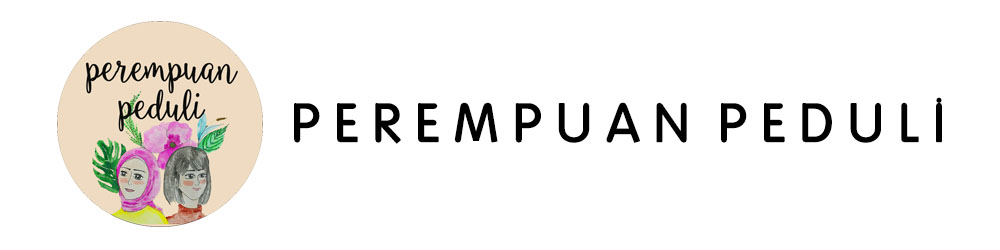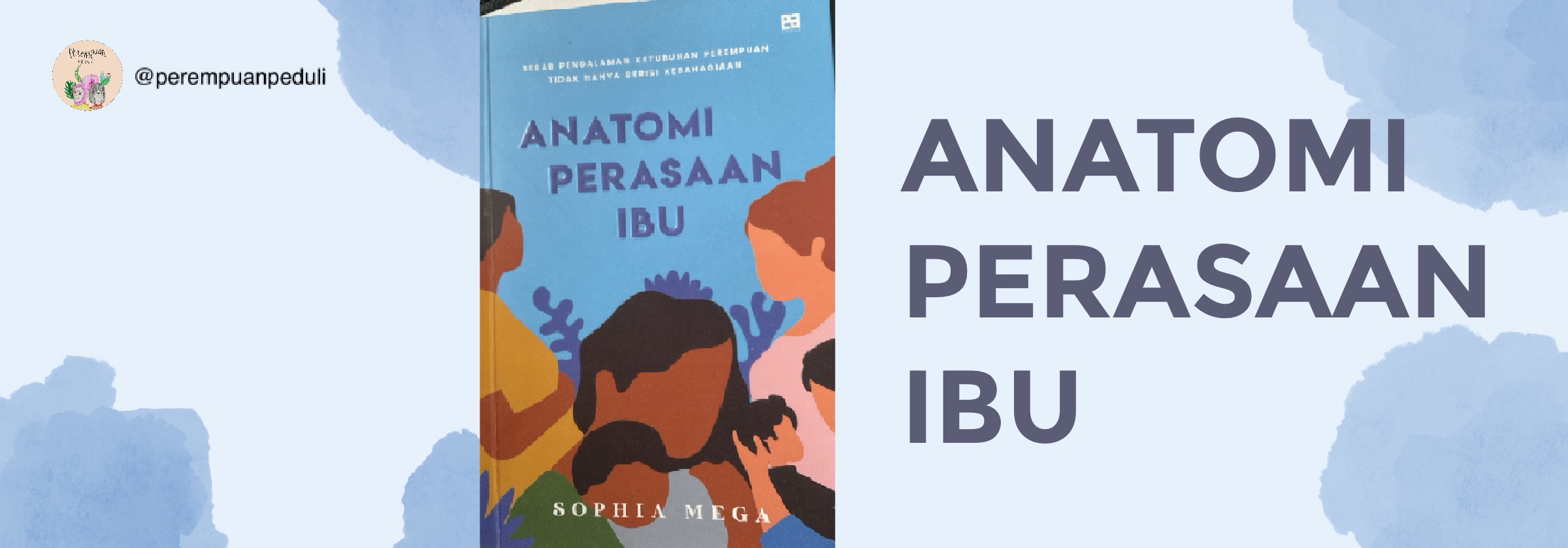Menulis Perempuan Melalui Karya Sastra (Novel “Si Parasit Lajang” Karya Ayu Utami)
“Tapi, ah ya, saya memang benci pada perkawinan yang menjadi status atau ukuran kebahagiaan manusia. Hey! Manusia boleh kawin, tapi tidak harus.” (Ayu Utami)
Novel “Si Parasit Lajang” merupakan salah satu rangkaian trilogi karya Ayu Utami yang dibuat pada tahun 2013. Berbeda dengan novel lain yang umumnya menceritakan tokoh perempuan sebagai sosok yang feminin, Utami lebih banyak bercerita tentang gugatan perempuan terhadap intitusi perkawinan, seksualitas, rasisme, kapitalisme, sosial, dan politik. Hal yang sangat menarik, Utami mencoba untuk membebaskan pikiran perempuan terlepas dari stereotipe yang berlaku dalam masyarakat. Istilah parasit lajang itu sendiri merujuk pada tokoh utama berjenis kelamin perempuan bernama A yang bekerja di kota metropolitan dan memutuskan untuk tidak menikah lalu tinggal dengan orang tuanya. Meskipun A telah bekerja, ia menggunakan fasilitas orang tua dan tidak terlibat dengan pekerjaan rumah, seperti membersihkan, merawat binatang peliharaan, hingga membayar listrik. Hal inilah yang dimaksud bagai benalu dalam keluarga. Adapun istilah parasit ini, tidak serta merta menunjukkan karakter A yang manja sekaligus bergantung kepada orang lain. A memiliki prinsip hidup dan mampu memutuskan sesuatu terlepas dari faktor eksternal di luar dirinya.
Pada bagian prolog berjudul “10+1 Alasan untuk Tidak Kawin”, A dengan tegas memberikan alasannya untuk tidak menikah. Beberapa di antaranya: tidak merasa perlu, tidak peduli, kepadatan penduduk, seks tidak identik dengan perkawinan, dan sudah terlanjur asyik melajang. Setiap poin memiliki argumen dan alasannya masing-masing. A ingin menggungat konstruksi dalam masyarakat bahwa pernikahan bukanlah tolak ukur kebahagiaan seorang perempuan. A mengharapkan perempuan bangun dari mimpinya sebagai Cinderella. Kisah percintaan pada umumnya berakhir dengan romantisme perempuan dan laki-laki, tetapi tidak menceritakan kehidupan selanjutnya (kehidupan pernikahan) yang mungkin belum tentu berbahagia untuk selama-lamanya.
Kehidupan pernikahan bagi A sangatlah rumit, karena di dalamnya terjadi perceraian, perkosaan domestik, kekerasan, perselingkuhan, dan anak-anak korban perceraian. Lebih lanjut, A memaparkan bahwa seorang perempuan harus dengan sadar mengambil pilihannya untuk menikah serta tidak bergantung kepada laki-laki. Artinya, pernikahan adalah sebuah pilihan yang dilakukan atas kesadaran (bukan paksaan) dan perempuan harus mampu menjadi independen dalam hidupnya.
Selain menggugat perkawinan sebagai sebuah keharusan, A ingin membongkar label kecantikan yang dihadirkan oleh pihak kapitalis melalui boneka Barbie. Boneka Barbie mampu menciptakan representasi kecantikan perempuan dan pada akhirnya terdorong untuk dapat tampil cantik layaknya Barbie.
“Karena itulah kritk para feminis terhadap Barbie berderet. Dia mereproduksi wacara patriarkal dan memperkuat hegemoni Barat. Dia menawarkan ideal kecantikan yang tidak realistis. Dia adalah anak panah kapitalisme.” (49)
Menurut A, boneka Barbie menjadikan perempuan sebagai korban kapitalisme. Perempuan mengubah dirinya menjadi diri yang lain, yaitu sosok boneka Barbie yang berkulit putih, berambut panjang, dan bertubuh langsing.
Dalam novel, A juga menceritakan tentang pentingnya pendidikan seks untuk perempuan. Selama ini seks dianggap tabu dan tidak dibicarakan dalam ruang pendidikan. Adapun informasi yang diberikan oleh pihak sekolah lebih memberikan ketakutan dan bukan informasi komprehensif mengenai seks itu sendiri. Berikut pemaparan A terkait pendidikan seks di sekolah:
“di SMP atau SMA, Tarakanita, barulah saya secara formal mendapat pendidikan tentang seks yang berhubungan dengan permukaan alat reproduksi…itu adalah foto-foto vagina yang terkena infeksi penyakit kelamin…Tetapi potret itu mengancam saya dengan rajasinga dan sipilis. Dan saya kira terapi kejut itu memang bagian dari konspirasi para pendidik untuk membikin kami takut bermain seks serampangan, sebab mereka malah tidak menjelaskan tetang keputihan – gangguan yang dialami wanita tanpa campur tangan (dan bukan tangan) laki-laki.” (123)
Berkaitan dengan seks, A menceritakan bahwa organ kelamin perempuan tidak lagi dianggap sebagai kelamin, melainkan alat kenikmatan laki-laki. Alasannya, karena seks bukan lagi menjadi sesuatu yang utuh dalam masyarakat patriarkal, sebagaimana kutipan berikut ini:
“sebagian dari organ seks wanita, misalnya klitoris dan konon G-Spot, bukan alat kelamin, melainkan alat kenikmatan belaka. Dia tak ada gunanya selain untuk bersenang-senang. Jadi, tidakkah legitimasi seks untuk prokreasi adalah sebuah konsep yang amat patriarkal?” (125)
A menginginkan perempuan dapat lepas dari belenggu prokreasi yang selama ini melekat pada tubuhnya. Perempuan harus memiliki tubuhnya tanpa terfragmentasi.
Berkaitan dengan perempuan dan sastra, Helene Cixous memiliki gagasan penting untuk membebaskan perempuan melalui tulisan. Dalam karyanya berjudul “The Laugh of the Medusa”, Cixous mengungkapkan bahwa perempuan harus menulis dirinya sendiri untuk membebaskan tubuhnya dan perempuan harus menempatkan dirinya ke dalam teks agar menjadi gerakan sejarah sendiri (877). Dasar Cixous mendorong perempuan untuk menuliskan dirinya karena struktur sosial tidak bisa dipisahkan dari struktur linguistik dan bahasa juga berkaitan dengan sejarah (Conley 4).
Selain itu, pendekatan penulisan laki-laki menggunakan oposisi biner yang mendikotomi karakter perempuan dan laki-laki dalam garis tegas (Arivia 130). Oposisi biner dalam hal ini bermakna perbedaan karakteristik yang tercipta dalam masyarakat patriarkal, antara perempuan dan laki-laki yang sangat bertolak belakang, seperti perempuan lebih perasa sementara laki-laki lebih kuat, perempuan bersifat pasif dan laki-laki aktif, perempuan adalah subjek dan laki-laki adalah objek, dan seterusnya. Oleh sebab itu, Cixous menantang perempuan untuk menulis dirinya keluar dari konstruksi yang membelenggu dirinya melalui kata-kata (Tong 292).
Bagi Cixous, tubuh perempuan harus didengar dan sebab itu perempuan harus menulis tubuhnya untuk memahami dirinya (Conley 62). Rekomendasi Cixous berupa penulisan perempuan (feminine writing) bertujuan untuk menghancurkan simbol bahasa maskulin (Humm 195). Sebagaimana dalam tulisan Cixous berjudul “The Helene Cixous Reader”, diungkapkan bahwa feminine writing dapat mengubah tatanan sosial dan politik yang menjadi dasar dalam kehidupan patriarkal dan kapitalis (xxix). Melalui feminine writing, perempuan dapat memberdayakan dirinya melalui minat tertentu serta dapat menekankan pentingnya sisi feminin yang positif, seperti toleransi, bebas tanpa batas mendalami seksualitas, erotisme, dan feminitas (Arivia 130).
Mengaitkan novel karya Ayu Utami dengan gagasan Cixous, novel “Si Parasit Lajang” berusaha untuk menuliskan tubuh perempuan secara bebas tanpa memedulikan oposisi biner yang hidup dalam masyarakat patriarkal. Tokoh utama A berani mengambil keputusan hidupnya untuk tidak menikah sebagaimana perempuan pada umumnya. Karya sastra lazimnya merujuk pada karakter perempuan yang feminin, pasif, lemah lembut, dan hal tersebut dibongkar oleh Utami melalui karakter A yang independen, aktif, dan mampu menjadikan dirinya sebagai subjek.
Tokoh A ingin menggugat konstruksi dalam masyarakat patriarkal yang menuntut perempuan untuk menikah dan menjalani fungsi reproduksi berupa prokreasi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Cixous, bahwa perempuan harus mampu menuliskan tubuhnya untuk memahami dirinya lebih mendalam. Perempuan harus menuliskan tubuhnya dan menempatkan dirinya ke dalam teks karena linguistik tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial. Utami dalam karyanya mencoba untuk mengeksplorasi diri perempuan melalui kebebasan berpikir, seperti perempuan tidak harus menikah, perempuan mempunyai hak atas ketubuhannya, perempuan memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi seksualitasnya, perempuan dapat menjadi sosok yang independen, serta perempuan harus mampu menjadi subjek dan bukan objek kapitalis.
Tokoh A sarat dengan penggambaran diri perempuan yang bebas dan independen tanpa menjadi “diri yang lain” melainkan diri yang utuh. Pada prolog “10+1 Alasan untuk Tidak Kawin” misalnya, A mempertegas dirinya untuk tidak menikah dan menjadikan hal tersebut sebagai pilihan (bukan keharusan). A menggambarkan dirinya sebagai sosok yang independen dan aktif dalam menghayati prinsip hidupnya. Sebagaimana dalam pemikiran Cixous, secara konvensional perempuan dikonsepkan sebagai sosok yang pasif dan sebab itulah dibutuhkan mediasi untuk memungkinkan terjadinya perubahan melalui tulisan (Conley 6-10). Dalam hal ini, karakter A sangat penting untuk dituliskan oleh perempuan itu sendiri untuk membongkar oposisi biner dalam masyarakat patriarkal. Tidak hanya itu, perempuan juga dapat membebaskan dirinya untuk tidak terjebak dalam kesadaran semu.
Utami dapat dikatakan sebagai penulis yang melakukan pendekatan feminist writing dalam karyanya. Bagi Cixous, feminine writing sangat penting untuk menghancurkan simbol bahasa maskulin, mengembangkan sisi feminin yang positif, serta mendalami tubuh perempuan secara bebas tanpa batas untuk menghancurkan struktur sosial dalam masyarakat patriarkal (Conley 62; Humm 195; Cixous xxix; Arivia 130).
Hal ini nampak pada beberapa kutipan novel “Si Parasit Lajang” di atas terkait beberapa hal. Pertama, keputusan terkait pernikahan. Tokoh A dengan bebas menjabarkan berbagai alasan untuk tidak menikah dan hal tersebut sangatlah prinsipil. A ingin mendobrak konstruksi dalam masyarakat yang mengharuskan perempuan untuk menikah. Perempuan diberikan label buruk apabila tidak menikah, seperti perawan tua, perempuan tidak laku, dan sebagainya. Padahal, pernikahan bukanlah menjadi keharusan bagi seseorang melainkan sebuah pilihan. Perempuan bebas untuk memutuskan sesuatu, terlepas dari faktor di luar dirinya. Pernikahan tidak menjadi tolak ukur kebahagiaan bagi perempuan. Gugatan itulah yang menjadi sangat penting untuk membangunkan perempuan dari kesadaran semu yang selama ini terpratri dalam masyarakat patriarkal.
Kedua, persepsi kecantikan berbalut kapitalisme. Boneka Barbie yang menjadi panutan kecantikan menyebabkan perempuan terjebak dalam kesadaran semu akan konsepsi kecantikan. Tidak hanya perempuan itu sendiri, konstruksi kecantikan yang diinternalisasi oleh masyarakat pada akhirnya menuntut perempuan untuk tampil cantik layaknya boneka Barbie, seperti bertubuh langsing, berkaki jenjang, berambut panjang, dan berkulit putih. Representasi kecantikan yang dihadirkan oleh boneka Barbie otomatis mengopresi perempuan dan bagi A kapitalis sangat mahir dalam membalut hasil produksinya.
Ketiga, pendidikan seks untuk perempuan. Intitusi pendidikan selama ini membuat seks menjadi tabu untuk dibicarakan. Adapun pendidikan seks yang diberikan adalah ketakutan-ketakutan (gambar penyakit kelamin) dan bukan pendidikan yang membangun pemikiran seseorang untuk memahami lebih dalam tentang seks. Menurut A, pendidikan seks sangat penting guna memperdalam pemahaman perempuan terhadap tubuhnya. Namun demikian, ketidakpahaman perempuan terhadap tubuhnya sendiri menyebabkan perempuan terjebak dalam kondisi pelik. Perempuan terfragmentasi dengan fungsi reproduksinya. Tubuh perempuan dianggap sebagai kenikmatan lelaki dan bukan kenikmatan untuk tubuhnya sendiri.
Gagasan Cixous mengenai feminine writing sangat penting untuk menyadarkan perempuan maupun laki-laki terhadap bias-bias gender. Karya-karya sastra yang sangat maskulin tentu saja mengkonstruksi pemikiran seseorang sekaligus memperkuat nilai patriarkal dalam masyarakat. Pada akhirnya, tulisan tanpa aspek feminine writing menyebabkan perempuan menjadi korban ketidakadilan, seperti subordinasi, kekerasan, maupun stereotipe. Oleh sebab itu, feminine writing sangat perlu digunakan untuk membebaskan perempuan dari stereotipe. Perempuan perlu memahami dirinya secara bebas sekaligus menggugat ketidakadilan dalam masyarakat yang patriarkal.
(Andi Nur Faizah)