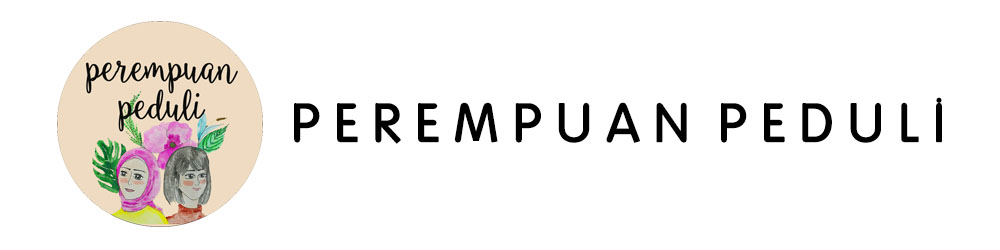Memaknai Konsep Keluarga Adil Gender (Part 1)
“Pasal-pasal dalam RUU ini (RUU Ketahanan Keluarga) mengukuhkan peran gender laki-laki dan perempuan yang bias, yang memosisikan laki-laki dalam wujud subjek yang “superordinat” yang bertindak sebagai pengambil keputusan utama… sementara perempuan sebagai istri dengan “subordinat” yang bertanggung jawab atas tugas-tugas rumah tangga”
Kutipan di atas adalah argumentasi Valentina Sagala dalam bukunya terkait analisis hukum
Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga. Ia mengungkapkan bahwa RUU tersebut justru melanggengkan ketimpangan gender yang menempatkan perempuan sebagai sosok terbelakang/ tidak penting (Sagala, 2020).
RUU Ketahanan Keluarga sempat ramai diperbincangkan sejak diusulkan oleh fraksi Golkar, PAN, PKS, dan Gerindra pada 7 Februari 2020 lalu. Dalam pasal 25 misalnya, disebutkan tentang pembagian peran yang saklek antara suami dan istri di dalam keluarga. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, sedangkan suami sebagai kepala keluarga berkewajiban untuk menjaga keutuhan dan kesejahteraan keluarga. RUU ini menuai kontroversi, sebab negara dianggap telah jauh masuk mencampuri kehidupan privat warga negaranya.
Siti Aminah Tardi selaku Komisioner Komnas Perempuan mengungkapkan, negara tidak boleh terlalu jauh masuk ke ruang privasi namun bukan berarti negara tidak boleh ikut campur. Negara boleh melakukan pengaturan terkait keluarga dan rumah tangga jika ada pelanggaran terhadap hak asasi, seperti KDRT, perdagangan orang, maupun pelanggaran HAM lainnya. Aminah yang saat ini menjabat sebagai Komisioner Sub Komisi Pemantauan tersebut menambahkan bahwa di dalam perkawinan dan rumah tangga tidak perlu ada kebijakan di luar konteks pelanggaran. Artinya, negara tidak dapat ikut campur terhadap nilai-nilai atau etika yang akan dibangun di dalam keluarga, sepanjang tidak melanggar HAM. Negosiasi pembagian peran antara suami dan istri dapat dilakukan sesuai kesepakatan masing-masing. Hal ini merupakan landasan penting sebab situasi setiap rumah tangga di Indonesia tidak dapat diseragamkan.
Situasi Keluarga yang Beragam
UU Nomor 1 tahun 1974 kerap menjadi acuan terhadap pembagian peran di dalam keluarga antara suami dan istri, sebab tertulis bahwa laki-laki sebagai kepala keluarga. Namun demikian, benarkah setiap keluarga dikepalai oleh laki-laki? Nyatanya, kondisi setiap keluarga di Indonesia sangatlah beragam. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, persentase perempuan kepala keluarga tahun 2018 berjumlah 15,17%. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 15,02% pada 2016 dan 14,63% pada 2015. Salah satu penyebab peningkatan angka perempuan kepala keluarga tersebut adalah permasalahan ekonomi di mana rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan umumnya merupakan kelompok termiskin di Indonesia.
Survei yang dilakukan oleh Perkumpulan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) bersama SMERU memperlihatkan bahwa perempuan menjadi kepala keluarga tidak hanya karena suami meninggal, bercerai, merantau, poligami, sakit, tua, atau disabilitas. Tetapi juga perempuan lajang yang memiliki anak ataupun menanggung beban ekonomi anggota keluarganya.
Data PEKKA (2010) menunjukkan, karakteristik perempuan kepala keluarga dengan kualitas rendah berusia antara 20 – 60 tahun, lebih dari 38,8% buta huruf dan dan tidak pernah duduk di bangku sekolah dasar (SD), menanggung 1 – 6 anggota keluarga, bekerja sebagai buruh tani atau sektor informal dengan pemasukan rata-rata kurang dari Rp. 10.000/ hari. Nani Zulminarni dalam wawancara mengungkapkan, secara statistik angka perempuan kepala keluarga meningkat. Namun bila turun ke lapangan maka terdapat fenomena gunung es, sebab indikator pengambilan data hanya mengacu pada kategori kepala keluarga adalah janda.
Padahal, tidak hanya perempuan janda yang menjadi kepala keluarga. Ada perempuan yang tidak menikah, ditinggal suami begitu saja, status menggantung karena suami pergi menghilang, dan ada juga suami yang sibuk dengan diri sendiri dan tidak menafkahi (Majalah Swara Rahima, 2010). Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa umumnya perempuan yang menjadi kepala keluarga terpaksa menjadi tulang punggung, karena suaminya meninggal dunia. “Tidak ada siapa-siapa lagi untuk mencari nafkah. Untuk mempertahankan kelangsungan keluarganya, mereka menjadi kepala keluarga. Kondisilah yang memaksa mereka untuk melakukan ini.” terang Nani.
Beragamnya kondisi keluarga tersebut memperlihatkan bahwa RUU Ketahanan Keluarga tidak bersifat inklusif. Pembagian peran antara suami-istri di dalam pasal 25 RUU Ketahanan Keluarga secara eksplisit mengabaikan situasi riil perempuan, pengalaman perempuan yang beragam, bahwa mereka memiliki kondisi yang tidak sama.
Dalam hal ini, pembagian peran antara suami istri tidak hanya mengeksklusi perempuan, tetapi
juga memberikan dampak serius terhadap kehidupan perempuan.
(Andi Faizah – Tulisan ini telah dipublikasi di Majalah Swara Rahima Edisi 57 Tahun 2020)