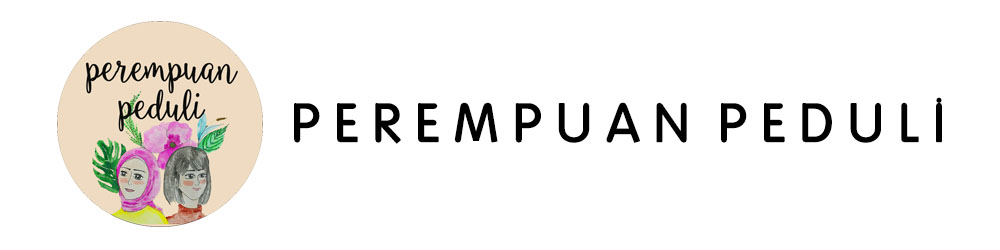Feminisme Liberal: Kritik untuk Sistem Pendidikan Diskriminatif di Indonesia
Revolusi Industri tahun 1759-1799 telah melatarbelakangi kemunculan Feminisme Liberal di Eropa. Kreativitas perempuan menurun karena mesin mengambilalih potensi perempuan. Hal itu berakibat pada kemunduran dan peminggiran posisi perempuan di Eropa. Pemikiran Feminisme Liberal hadir untuk memberikan pandangan tentang kebebasan individu (laki-laki atau perempuan) untuk meraih tujuan dan nasib sendiri sesuai dengan rasio. Semangat dari gerakan feminis liberal adalah kebebasan perempuan dan laki-laki yang mendapatkan pola asuh yang sama sejak dini. Singkatnya, tujuan dari Feminis Liberal meliputi kebebasan individu (tidak saling menutupi potensi), aturan dan akses yang adil berlaku untuk perempuan dan laki-laki di semua bidang. Lalu, bagaimana implementasi mimpi Feminisme Liberal di Indonesia?
Gerakan Feminisme Liberal memang sudah berkembang sejak abad ke-18. Tetapi diskriminasi perempuan masih tetap terjadi khususnya di Indonesia. Ada banyak kasus yang muncul di negeri ini. Saya tertarik untuk membahas tes keperawanan sebagai salah satu syarat masuk sebagai peserta didik (kadet) Polisi Wanita Republik Indonesia. Berita ini muncul di berbagai media cetak dan elektronik sejak tahun terutama tahun 2014. Namun, saya pribadi sudah mendengar berita tersebut sejak zaman SD (sekitar tahun 2000-an). Ironisnya, kasus tersebut masih simpang siur dan tidak menemukan penyelesaian jelas di masyarakat hingga saat ini. Bahkan, ada opini di masyarakat bahwa tes keperawanan sudah jadi syarat wajib pendidikan bagi Polisi Wanita yang tidak perlu dituliskan. Saya menekankan bahwa tes keperawanan adalah bukti nyata diskriminasi bagi perempan di ranah pendidikan Indonesia.
Sekali lagi, opresi juga terlihat pada proses pengecekkan keperawanan dengan cara memasukkan 2 jari tenaga kesehatan ke dalam lubang vagina peserta perempuan. Tujuannya, mengetahui selaput darah calon peserta masih utuh atau sudah robek. Tentu saja cara tersebut sudah menimbulkan trauma dan rasa sakit bagi perempuan. Terlebih bagi peserta yang tidak lolos ujian dengan salah satu alasan karena sudah tidak perawan. Bisa dibayangkan penderitaan perempuan akibat tekanan dari keluarga dan lingkungan sekitar. Adanya diskriminasi yang berlangsung belum mampu menjawab mimpi Feminis Liberal yang menginginkan kesamaan seluruh perlakuan bagi perempuan dan laki-laki di dunia pendidikan (Wollstonecraft dalam Putnam Tong, 22).
Faktanya, tes keperawanan ini benar-benar pernah membunuh mimpi seorang perempuan untuk mengabdikan dirinya kepada negara. Saya memiliki pengalaman langsung dengan seorang sahabat saat duduk di bangku perkuliahan sebelumnya. Bagi saya, dia termasuk perempuan pintar dan cerdas. Dia bercerita bahwa sebelumnya sangat berkeinginan untuk menjadi Polisi Wanita. Dia menganggap profesi ini merupakan kebanggan bagi keluarga dan dirinya pribadi. Namun, karena mengetahui dan mendengar berita tentang tes keperawanan tersebut dia menjadi sangat takut. Ternyata, dia pernah menjadi korban pemerkosaan pada saat SMP oleh pacarnya. Akibatnya, saat dia bercerita untuk mengurungkan niat sebagai Polwan kepada keluarga, dia dan keluarganya mengalami kekecawaan mendalam. Sekali lagi, hanya karena dia merasa dirinya tidak perawan. Lalu, kapan pendidikan di Indonesia akan lebih maju jika masih dikaitkan dengan norma fiktif demikian?
Pertanyaan saya selanjutnya adalah mengapa ada tes keperawanan namun tidak ada tes keperjakaan? Jelas, tidak ada perlakuan setara antara laki-laki dan perempuan di pendidikan Indonesia. Tes keperawanan perempuan masih terjadi karena dianggap wajar bahwa hanya perempuan “baik-perawan” yang bisa masuk menjadi calon Polisi Wanita. Dengan kata lain, perempuan yang sebelumnya pernah menjadi korban pemerkosaan tidak berhak untuk memiliki pendidikan sebagai Polisi. Hal itu jelas bertentangan dengan prinsip Feminisme Liberal yang memberikan kebebasan siapapun untuk bisa mencapai mimpi dengan nalar serta kemampuan diri sendiri. Dari diskriminasi yang ada, lagi-lagi perempuan tidak bisa bebas menyampaikan pendapat, menolak dan menuntut perlakuan diskriminatif tersebut untuk dihapuskan.
Saya juga melihat bahwa istilah Polisi Wanita juga menjadi bias tersendiri. Dalam hal ini ada pembeda istilah “Wanita-Polwan”, sementara tidak ada sebutan untuk Polisi Pria atau Laki-laki. Kondisi demikian menunjukkan masih adanya upaya pembedaan baik di ranah (pendidikan/pelatihan) akademisi maupun profesi sektor public bagi Polisi. Feminisme Liberal berharap bahwa pendidikan antara perempuan dan laki-laki harus sama. Taylor dan Mill sepakat bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa perempuan memiliki nalar yang lebih rendah dibandingkan laki-laki (Mill dalam Putnam Tong 40). Sementara, posisi Polisi Wanita juga masih terkesan berada dibawah Polisi berjenis kelamin laki-laki. Hal itu diperkuat dengan adanya bukti bahwa pemimpin tertinggi di lembaga kepolisian selalu di dominasi oleh laki-laki dari dulu hingga sekarang. Hal itu merupakan bukti adanya pembedaan seksual yang berimplikasi terhadap bias gender dalam profesi.
Berdasarkan penjelasan Feminis Liberal (Friedan dalam Humm 182), diskriminasi tes keperawanan dapat dihapuskan melalui kebebasan serta keberanian perempuan untuk lantang menolak praktik diskriminasi. Saya meyakini bahwa selaput darah adalah hak pribadi dan tidak berkaitan dengan keperawanan. Terlebih, keperawanan tidak berhubungan kengan kualitas seorang perempuan. Pun tidak ada perbedaan kemampuan antara laki-laki dan perempuan secara biologis. Oleh karena itu penolakan harus dilakukan. Tes keperawanan hanya menjadi salah satu penghambat perempuan untuk berkompeten di bidangnya. Karena ada rasa takut bagi mereka yang sebelumnya merasa sudah tidak perawan. Akibatnya, lembaga kepolisian tidak memiliki orang yang seharusnya kompeten. Hal lain untuk menyelesaikan diskriminasi ini adalah intervensi negara juga diperlukan untuk menata aturan yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Hal itu selaras dengan pendapat Feminism Liberal yang merujuk pada Liberalisme Kesejahteraan bahwa negara perlu mengatur dan memberikan intervensi atas kebijakan yang dianggap mengerdilkan satu pihak.
Selain kebebasan perempuan dan intervensi negara untuk menolak system tes keperawanan, androgini juga menjadi salah satu tawaran alternative dari Feminisme Liberal Kontemporer untuk meminimalisir adanya bias gender di dunia lembaga kepolisian (Friedan dalam Tong 46). Polisi perempuan dapat memiliki sisi maskulin dan Polisi laki-laki memiliki sifat feminine baik secara tampilan maupun karakter. Gabungan kekuatan sisi feminine dan maskulin menjadikan perempuan tidak harus berubah menjadi laki-laki dan begitu pula sebaliknya. Hal demikian dapat menjadi satu langkah untuk mewujudkan masyarakat yang adil tanpa ada diskriminasi dan pembedaan secara seksual maupun gender.
Pemikiran dan gerakan Feminisme Liberal masa itu telah menjadi acuan pemikiran kritis yang mempertanyakan kembali posisi dan status perempuan yang terdiskriminiasi. Hal itu menjadi kekuatan awal untuk pemikiran feminism selanjutnya. Saya berfikir bahwa sebagai awal gerakan feminism, konteks yang disampaikan oleh tokoh-tokoh Feminsme liberal sangat komprehensif dan memiliki sensitivitas keberpihakan kepada perempuan yang tinggi. Karena isu berkaitan pendidikan, politik, hukum hingga hal sipil menjadi sorotan utama untuk upaya pembebasan dan penghapusan segala bentuk opresei kepada perempuan di masa itu dan saat ini. Mereka juga berani mendobrak status quo perempuan borjuis yang dianggap terlalu manja dan bergantung kepada suami. Hal itu memberikan penyadaran bagi perempuan agar bisa mandiri dengan nalar dan potensi yang ada.
Pemikiran Feminisme Liberal kontemporer justru mengabaikan kebebasan individu yang menjadi semangat utama Feminisme Liberal. Hal itu terlihat dalam pemikiran abad 21 karena mereka cenderung kebingungan apakah perempuan harus berperan di ranah domestic atau public. Kebingungan tersebut berujung pada munculnya beban kerja ganda di perempuan karena harus mengurus keluarga dan mencari nafkah. Selain itu, pembahasan feminism liberal juga belum belum membahas tentang bagaimana perempuan miskin dapat mencapai tujuannya. Mereka hanya menjelaskan kalangan menengah dan borjuis. Mill juga memiliki pandangan yang bias karena belum bisa melepaskan diri dari pandangan bahwa perempuan memiliki kewajiban untuk membesarkan anak dengan lebih baik dibanding laki-laki (Mill dalam Putnam Tong 29). Saya merasa bahwa kebebasan yang digaungkan dalam awal pemikiran Liberal menjadi kurang nampak. Padahal, liberalism sudah dengan jelas menyatakan bahwa semuanya berasakan kebebasan. Jadi masih ada pandangan yang saling bertumpang tindih.
Kasus tes keperawanan adalah satu dari berbagai kasus diskriminasi, peminggiran dan opresi bagi perempuan di Indonesia. Saya rasa kasus diskriminasi ini menjadi contoh betapa lemahnya system pendidikan di Indonesia yang masih menjunjung perawan dan tidak perawan untuk menentukan kualitas perempuan. Padahal konsep perawan dan tidak perawan sendiri juga sangat perlu ditanyakan atau dicari tahu penyebab sebelumnya. Namun, penghakiman dan stigma seringkali langsung diterima perempuan karena sudah dianggap tidak perawan (karena selaput darah yang robek). Sementara, laki-laki justru dengan seenaknya bisa hidup dengan tenang tanpa dibayangi rasa takut istilah perjaka dan tidak perjaka. Jadi, saya menegaskan bahwa ketidakadilan pada perempuan akan terus muncul di Indonesia jika kita tidak melawannya sejak sekarang.
(Fitria Sari)
Daftar Pustaka:
Humm, Maggi (ed). 1992. Feminism A Reader. London: Harvester Wheatsheaf Press
Tong, Rosmarie Putnam. 1988. Feminist Thought a more comprehensive introduction (sec.dition). Colorado: Westview Press (terjemahan Aquarini Priatna Prabasmoro)
Watkins, Susan Alice dkk. 2007. Feminisme Untuk Pemula. Yogyakarta: Resist Book
www.jpnn.com. Tes dua jari bagi Polwan-26 November 2014. Didownload pada Kamis, 15 September 2016 jam 17.35 WIB