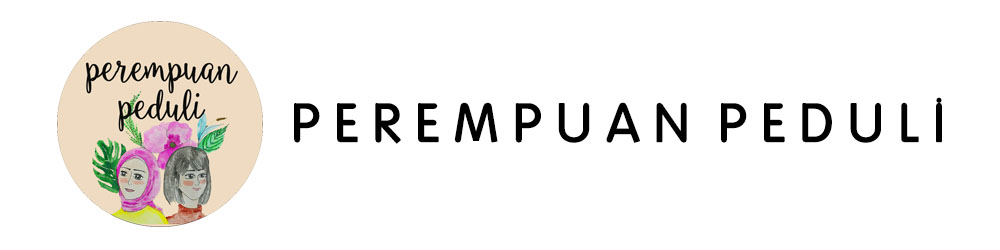Otonomi Tubuh Perempuan: Milik Siapa?
Saya ingat bagaimana kakak dari teman saya berani memegang payudara saya ketika saya berumur 5 tahun. Bagaimana dia berani mengajak saya untuk bermain sepeda lalu mengajak saya ke tempat yang cukup jauh dari rumah. Anak sekecil itu berteriak dalam hati karena tidak berani bicara. Jiwa ini seolah absen dalam kehadirannya sebagai pemilik tubuh. Saya ingat bagaimana teman dari kakak saya sengaja memegang sekujur tubuh saya ketika saya berumur 8 tahun. Saya terbangun dia mengatakan satu kalimat yang tidak pernah bisa saya lupakan “kenapa bangun? Tidur gih, katanya ngantuk.” Keparat laki-laki itu menyentuh sekujur tubuh saya(IA 2016, suara hati 23-24 September).
Saya ingat betul IA tak kuasa menahan tangis saat membaca suara hati yang ia tulis dalam makalah berjudul “Budaya Pemerkosaan Dalam Sudut Pandang Feminisme Psikoanalisis: Opresi Terhadap Kepribadian Anak Perempuan” pada kegiatan Konferensi Internasional yang diselenggarakan oleh Jurnal Perempuan. IA juga sempat menceritakan bahwa pelaku melakukan hal yang sama kepada adik kandungnya sendiri. Dalam hal ini, kekerasan seksual terjadi di dalam rumah dan pelakunya adalah orang terdekat. IA berargumen dalam makalahnya, pemerkosaan dilanggengkan akibat patriarki yang begitu kuat dalam masyarakat dan menjadikan pemerkosaan sebagai sesuatu yang wajar.
Argumen IA mengingatkan saya kepada seorang teman (berjenis kelamin laki-laki) yang mengatakan bahwa seorang perempuan berpakaian seksi wajar diperkosa. Menurutnya, perempuan tersebut salah karena telah mengundang hasrat laki-laki dan merupakan kesalahan apabila perempuan berpakaian terbuka. Jadi, wajar adanya apabila perempuan tersebut diperkosa. Isu mengenai pemerkosaan ini juga dibincangkan dalam media sosial seperti facebook dan instagram. Misalnya, terdapat gambar permen dengan lalat di sekitarnya. Permen tersebut diasosiasikan sebagai perempuan dan lalat sebagai laki-laki. Permen yang tidak dibungkus akan dihinggapi lalat, sementara permen yang dibungkus tidak akan dihinggapi lalat. Gambar tersebut menunjukkan, perempuan yang berpakaian terbuka akan rentan digoda oleh laki-laki sedangkan perempuan yang menutup seluruh tubuhnya dengan gamis dan jilbab tidak akan digoda laki-laki. Penggambaran yang sangat dangkal tersebut diamini oleh masyarakat dan merupakan kewajaran apabila seorang perempuan yang berpakaian terbuka akan digoda bahkan diperkosa oleh laki-laki.
Permasalahan pakaian perempuan tidak hanya ramai dibicarakan dalam ruang media sosial. Negara juga ikut andil dalam mengatur tubuh perempuan melalui berbagai cara. Pertama, melalui aturan daerah yang mewajibkan perempuan untuk berbusana muslim (mengenakan rok dan jilbab), tidak boleh mengenakan celana, hingga aturan jam malam. Kedua, melalui aturan sekolah negeri yang saat ini mewajibkan seluruh muridnya mengenakan pakaian muslim pada hari Jumat. Laki-laki mengenakan baju muslim dan perempuan mengenakan rok panjang serta jilbab.
Ketiga, melalui aturan sensor yang dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Belahan dada perempuan yang nampak akan diblur, tokoh film kartun yang mengenakan pakaian renang akan diblur, hingga anak sekolah yang memerah susu sapi juga diblur. Hal yang dapat dilihat dalam kasus ini, negara berusaha untuk mengontrol tubuh perempuan. Melihat ketiga kasus di atas, membuat saya bertanya-tanya, mengapa perempuan menjadi korban, disalahkan, sekaligus tidak mendapatkan keadilan?
Menurut Millett, opresi perempuan berakar pada konstruksi gender yang berada dalam sistem patriarki. Lebih lanjut, Millett mengungkapkan bahwa seks adalah suatu hal yang politis (Tong 73). Politik dalam konteks ini merujuk pada relasi kuasa, sekelompok orang yang dikontrol oleh pihak lain, politik seksual seseorang terhadap dirinya (Millett 23-24). Jadi, dalam hal ini relasi politik adalah hubungan kuasa yang berada dalam relasi seluruh manusia dan mengatur seseorang atau sekelompok orang (McCaann dan Kim 18). Bagi Millett, penguasaan terhadap orang lain (power over) harus dihapuskan, karena seseorang harus menunjukkan dirinya secara bebas terlepas dari kuasa siapapun.
Ketiga kasus beserta pertanyaan saya di atas, dapat dihubungkan dengan argumen Millett, bahwa perempuan mendapatkan penindasan karena adanya relasi kuasa yang hidup dalam ideologi patriarki. Keluarga, masyarakat, dan negara berkontribusi dalam mengontrol tubuh perempuan dengan berbagai cara. Perempuan dianggap sebagai sosok yang harus patuh. Tubuh perempuan juga dipandang sebagai “penggoda hasrat” dan sebab itu harus dikontrol. Pada kasus di atas, di dalam rumah seorang anak perempuan tidak punya kuasa atas tubuhnya hingga dijamah oleh laki-laki yang lebih tua darinya.
Kemudian pada kasus lingkungan masyarakat, pemerkosaan menjadi suatu hal yang wajar karena perempuan yang berpakaian terbuka akan memancing hasrat laki-laki. Masyarakat punya kuasa untuk mengontrol sekaligus memberikan penghakiman kepada perempuan. Power over juga kemudian dilanggengkan oleh negara melalui peraturan yang diskriminatif terhadap perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa jenis kelamin (sex) memberikan dampak atau implikasi politik (Humm 62). Relasi kuasa yang berada di dalam keluarga, masyarakat, dan negara ingin mengatur atau mengontrol tubuh perempuan.
Pada akhirnya, penindasan yang bersifat privat juga terjadi dalam ranah publik (Arivia 101). Sebagaimana yang diungkapkan oleh McCann dan Kim, personal is political tidak terbatas pada relasi privat saja, tetapi juga meluas pada praktik institusional yang mengatur kebebasan perempuan di ranah publik hingga merasuk ke ranah privat (19). Artinya, perempuan terenggut otonomi atas tubuhnya akibat relasi kuasa yang berada di luar tubuhnya dan sebab itu perempuan harus melawan isu personal tersebut.
Relasi kuasa keluarga, masyarakat, dan negara pada akhirnya menimbulkan ketidakadilan terhadap perempuan. Pertama, perempuan yang mengenakan pakaian terbuka mendapat stereotype sebagai perempuan “nakal”, “binal”, bahkan dianggap wajar bila diperkosa. Kedua, kekerasan terselubung (molestation) dialami oleh perempuan. Seperti pada kasus IA, bagian tubuhnya disentuh oleh laki-laki tanpa seizin darinya. Ketiga, pelecehan seksual atau sexual and emotional harassment seringkali dialami oleh perempuan. Bentuk pelecehan yang paling sering terjadi adalah unwanted attention from men (Fakih 20). Tindakan yang tidak menyenangkan ini berupa candaan seksis maupun godaan berupa siulan kepada perempuan yang sedang berjalan di pinggir jalan.
Pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah, mengapa ketidakadilan terhadap perempuan masih saja terjadi? Dalam hal ini saya ingin menggunakan pemikiran Foucault tentang diskursus. Diskursus mengonstruksi dan dikonstruksi melalui praktik sosial, lembaga, bahasa dan selanjutnya dianggap sah sebagai pengetahuan (Fakih 169). Diskursus juga merupakan himpunan pernyataan yang berdialog secara terus menerus dimediasi melalui teks antara permbicara dan pendengar terpisah dari satu sama lain dalam ruang dan waktu (Smith 161).
Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa diskursus hadir dalam tiap aspek kehidupan masyarakat dari satuan unit terkecil seperti keluarga hingga negara. Nilai-nilai patriarki berbalut agama masuk sebagai pengetahuan dan diamini sebagai sesuatu yang benar. Kemudian pengetahuan tersebut disebarluaskan melalui institusi pendidikan non formal (keluarga) dan formal (sekolah). Hasrat kuasa akan tubuh perempuan juga dilanggengkan melalui gambar maupun teks yang berada dalam ruang media sosial.
Smith mengungkapkan, kelompok diskursus mengorientasikan diskursus melalui pembicaraaan, menulis, dan membuat gambar sebagai bentuk capaiannya (161-162). Hal ini nampak jelas pada contoh sebelumnya mengenai permen dan lalat, pemahaman tersebut dikonstruksi dan diterima sebagai pengetahun yang benar. Representasi yang diciptakan oleh media tersebut menyajikan realisme. Realisme ini kemudian mengaburkan kesadaran dan kita menerimanya sebagai kaca realitas (Arivia 25). Hasrat kuasa akan tubuh perempuan selanjutnya dilegitimasi oleh negara berupa peraturan-peraturan yang dianggap baik untuk mengontrol perempuan.
Ketidakadilan terhadap perempuan juga semakin langgeng melalui internalisasi ideologi patriarki berbalut agama terhadap perempuan itu sendiri. Perempuan menghayati dirinya sebagai sosok yang lemah lembut, penurut, dan perlu mendapat perlindungan. Pemahaman tersebut membuat kesadaran semu dan bukan menjadi kesadaran kritis. Oleh sebab itu, kontrol negara terhadap tubuh perempuan dianggap wajar. Wajar adanya perempuan dilecehkan saat menggunakan pakaian yang terbuka. Oleh sebab itu, perempuan harus menutup tubuhnya rapat-rapat dengan mengenakan busana muslim (baju gamis dan jilbab). Berbagai bentuk kontrol yang diberikan kepada perempuan dimaknai sebagai bentuk perlindungan. Hal ini juga yang membuat opresi terhadap perempuan masih terjadi.
Menurut saya, Millett telah membuat langkah besar untuk menjelaskan akar permasalahan dari opresi perempuan. Relasi kuasa yang terjadi pada perempuan masih sangat relevan untuk menjelaskan fenomena masa kini. Namun demikian, seberapa pun kuatnya perempuan untuk meraih haknya terhadap otonomi tubuh sebagaimana yang diungkapkan oleh Millett, perlu disadari bersama bahwa untuk menciptakan keadilan juga dibutuhkan sinergi dengan laki-laki. Kesadaran kritis perlu dibangun bersama (perempuan dan laki-laki) untuk membebaskan perempuan dari segala bentuk penindasan serta mengembalikan hak atas tubuhnya sendiri.
(Andi Nur Faizah)